Kompleksitas Emosi : Tahap Menerima dan Mencerna yang Lebih Sulit dari Tahap Merasa
 |
| credit |
“The world as we have created it is a process of our thinking. It cannot be changed without changing our thinking.” –Albert Einstein
Kutipan Albert Einstein di atas kayaknya bisa dinobatkan jadi kutipan yang paling bikin ngangguk-ngangguk dan bergumam, "Iya juga ya," sampai di titik ini. Delapan belas tahun hidup dan yang paling kerasa di aku sendiri adalah bagaimana cara kita berpikir, specifically dalam postingan ini di masalah mengolah perasaan, ternyata merupakan hal yang krusial.
Makin kesini, makin banyak kejadian-kejadian yang datang dan alhasil bikin mikir seribu kali tentang apa-apa yang dirasa. Sebutlah semakin besar semakin banyak ketemu orang, semakin banyak masalah yang datang dan harus dihadapi, dan sebagainya. Nggak lupa bahwa fenomena manusia yang makin banyak berselancar di dunia maya bikin aku pribadi merasa bahwa, "Oh ada ya orang yang seperti ini," (atau kalau lagi gemes, "Kok bisa sih ada orang mikir gini?!") tiap baca suatu gagasan atau ide yang di idealisme aku sendiri nggak sesuai.
One thing for sure : Manusia (dan pikirannya) memang seberagam itu.
 |
| credit |
Ketemu sama hal-hal beginianlah yang akhirnya sadar nggak sadar ternyata juga bikin aku (atau mungkin teman-teman lain juga kalau ada yang merasa hal yang sama) jadi nge-input segala emosi ke hal-hal yang dihadapi. Kita bisa setuju sih kayaknya kalau emosi yang kita rasa ketika pertama kali merasakan sesuatu itu ya hal yang reflek. Ibarat kalau lagi megang permukaan gelas yang isinya air panas, tangan kita sendiri reflek menjauh. Dalam artian, ya memang nggak bisa menyalahkan, dan nggak akan ada poinnya juga memaksakan dan menghakimi suatu hal yang reflek.
Namun, poin yang jadi masalah, setidaknya yang aku rasakan, adalah bagaimana kelanjutannya kita bersikap atas pikiran dan perasaan tersebut? Merasa itu tahap yang mudah, tapi bisa mengalokasikan perasaan dan bertindak dengan tepat setelahnya itu yang jadi peer paling berat.
Berdamai dengan semua emosi makin kesini jadi hal yang sulit karena banyak kesempatan dimana aku sendiri merasa bingung harus memfokuskan diri ke perspektif yang mana. Gimanapun, manusia pasti punya emosi negatif yang dirasa, begitu juga aku, dan dengan ilmu bahwa katanya manusia nggak disarankan untuk denial sama perasaannya (dan aku setuju), maka pertanyaan, "Terus ini harus gimana biar nggak toxic tapi tetep bijak memilih sikap?" jadi penting buat aku pribadi.
Sembari bertumbuh besar, nampaknya jawaban-jawaban dari beberapa kegalauan di atas sedikit demi sedikit agak terjawab dan aku merasa tercerahkan, terutama malah di hari-hari quarantine di tengah pandemi ini.
Maka, hal pertama yang aku pelajari adalah :
Emang gimana sih sosok dirimu, menurut perspektif kamu sendiri? Apa yang mau diperbaiki?
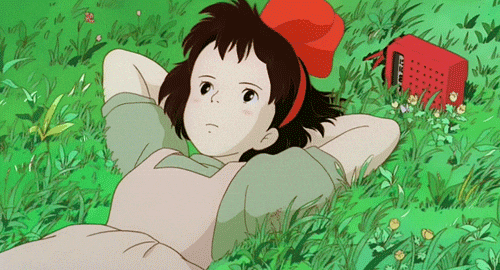 |
| credit |
Memperbaiki diri sendiri juga nggak akan ketemu jawabnya kalau kita nggak tahu hal apa yang perlu diperbaiki. Sampai akhirnya aku sadar betapa aku sendiri tipikal yang sangat-sangat-sangat emosional dan melankolis. Nasihat paling susah dari teman sampai sekarang masih nasihat, "Yaudahlah, nggak usah dimasukin ke hati," karena in fact, I take things deeply.
Masalah kedua : I absorb people's feelings–almost like a sponge. Sebenernya seneng-seneng aja sih punya kepribadian begitu karena rasanya bisa mudah memosisikan diri ke orang lain, namun nggak baik juga lama-lama karena nggak lucu ya kalau aku sendiri bisa lebih sedih daripada orang yang sedang sedih dan cerita ke aku. Dalam sisi lain, lama-lama kerasa efek buruknya yaitu lebih berasa asing sama diri sendiri karena jatohnya malah sering menduakan emosi personal dan mengutamakan emosi sekitar. Without trying to sound selfish, it is actually a problem in my own perspective since I often feel lost and confused about things that happen inside me.
Pada intinya, aku sadar bahwa yang aku butuhkan adalah kemampuan self-control yang baik. Manajemen pikiran dan hati yang baik. Tahu kapan harus meng-invest waktu dan pikiran yang kompleks untuk suatu hal yang memang worth-it dalam jangka panjang, tahu bagaimana harus bersikap, dan juga tahu batasan diri dalam merasakan emosi tertentu.
Satu hal yang dipelajari juga, ternyata kemampuan self-control, manajemen hati, dan manajemen pikiran yang baik itu bukan sesuatu yang gifted (karena kalau iya maka terpujilah orang yang dianugerahi kemampuan tersebut). Kita semua bisa setuju kalau kemampuan tersebut merupakan hasil dari proses panjang refleksi diri dan pintar-pintar memilih lesson-learned dalam memandang segala hal yang terjadi di hidupnya. Hence, I started to keep that in mind.
Namun, sungguh, praktiknya lebih susah daripada yang dibayangkan.
 |
| credit |
Karena di kenyataannya, banyak banget emosi-emosi yang nggak terduga yang datang. Pernah nggak lagi baik-baik aja tiba-tiba gloomy sendiri? Lagi ketawa-ketawa sama temen atau keluarga tiba-tiba sedihnya muncul? Perasaan-perasaan yang irasional dan nggak nyampe logika kalau ditelaah, "Ini datengnya dari mana, sih?!"
Kabar baiknya, I also learned the very important thing:
Proceeding your feeling starts with acknowledging and accepting it.
Atau singkatnya : Yaudah. Terima. Aja.
Kuncinya bisa dibilang ternyata ada di situ. Ibarat makanan, kita nggak akan bisa mencerna suatu makanan kalau kita nggak menerima dan mau buka mulut untuk masukin makanannya. Ibarat tamu, kita nggak bisa paham tujuan tamu itu datang kalau nggak menerima dan mau bertanya serta menelaah maksudnya datang apa.
Ditambah pembelajaran bahwa kita sah-sah aja kok kayaknya ngerasain semua emosi. We are allowed to feel anything. Anything.
Pemahaman ini penting menururut aku sendiri biar nggak jadi toksik ke diri sendiri maupun memaksakan harus jadi pribadi yang positif setiap saat. Nyatanya, kita nggak bisa tahu definisi perasaan positif kalau nggak ada perasaan negatif. Nyatanya, kita butuh-butuh juga perasaan yang terkesan negatif. Sebutlah takut, ragu, insecure, dan segala macam lainnya. Kalau dipikir lagi, perasaan-perasaan tersebut yang bikin kita berkembang dan sadar untuk maju serta menambah wawasan lagi. Kalau nggak ada perasaan yang terkesan negatif tersebut, nggak ada ruang untuk meng-improve diri dan tahu letak kekurangan kita. Iya kan, ya? *loh terus monolog gini*
Mungkin peernya adalah gimana kita bisa mengalokasikan itu dengan tepat. Apakah dengan cerita ke orang terdekat, nulis, atau hal lainnya. Bertindak dalam rangka mengalokasikan energi negatif ini juga ternyata harus hati-hati, ya, huhu. Biar nggak kemakan emosi dan malah jadi dikontrol oleh emosi tersebut. Pula nggak gegabah dan mengakibatkan kerugian ke diri sendiri dan orang lain. Pembelajaran biar jadi manusia yang pinter mengendalikan emosi emang berat, ya, ternyata. Namun semoga kita bisa, deh, ya, belajar mengalokasikan emosi dengan tepat.
 |
| credit |
Poin terakhir, balik lagi ke masalah pikiran 'reflek' kita–yang tadi dibahas di paragraf awal. Pikiran pertama yang terlintas di otak kalau ngelihat sesuatu. Satu yang aku pelajari, first thought is unpredictable. Makanya mustahil kayaknya kalau memaksakan diri buat punya pandangan yang langsung 'final' kala melihat sesuatu pertama kali.
Namun, kayaknya hal tersebut nggak masalah karena tadi habis lihat quote,
"Your first thought is what society has conditioned you to think, the second thought defines who you are."
Alias kayaknya kita nggak perlu terlalu memusingkan pikiran pertama yang terlintas, kalaupun perlu, maka bisa dipikirkan, "Kok aku reflek mikir kaya gitu berarti kebentuk dari mana ya?". Namun lebih penting untuk mencerna lagi hal tersebut dan kasih waktu untuk diri sendiri untuk berpikir secara objektif (karena di aku, first thought itu biasanya jatohnya sangat subjektif). Di sini, kemampuan critical thinking (yang masih sangat aku pelajari) dan juga empati, jadi penting dalam membentuk opini pribadi.
 |
| credit |
-------------------
Pada intinya, the way we think and proceed our emotion is crucial. Kenapa? Karena, it will lead to the response and action that we give. Kalau salah, penyesalannya bisa lama. Nulis ini karena sebenernya jadi self-reminder juga untuk bisa lebih bijak dalam memilah emosi dan pikiran yang mau dirasa. Membedakan mana yang sebaiknya dikeluarkan dan mana yang enggak. Kemampuan mengolah emosi atau emotional intelligence ini ternyata krusial dan nggak kalah penting sama kecerdasan intelektual.
Meski susah, namun semoga, kita selalu dekat dengan pembelajaran-pembelajaran dalam mengolah emosi yang baik, ya!
Warm regards,
Oni.
aku baru baca buku filosofi teras, dan relate sama yang kamu tulis ini on, sering-sering bikin ginian on biar aku ada bahan bacaan buat menikmati senja hehehee, ya kayak yang pernah dibilang mbah sujiwo tejo; "negeri ini kebanyakan pagi, kekurangan senja, kebanyakan gairah, kurang perenungan". semangat di negeri sakura oni💪
BalasHapus